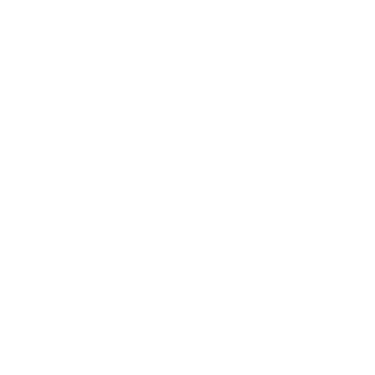Suku Sentinel yang Memilih Tetap Primitif di Era Modern
SEJARAHALAM
Regina R. Novanka
11/3/20252 min read


Bayangkan punya tetangga yang selama 60.000 tahun menolak kedatangan siapa pun. Setiap kali ada yang mencoba berkunjung, mereka sambut dengan hujan panah. Itulah kehidupan sehari-hari suku paling terisolasi di Bumi: Suku Sentinel, penghuni Pulau Sentinel Utara, titik hijau kecil di Samudra Hindia yang tak pernah benar-benar tersentuh dunia luar.
Nama pulau ini mungkin sudah sering melintas di media sosial seperti TikTok, YouTube, atau Instagram karena kisahnya yang nyaris tak masuk akal. Ketika kita mulai tertawan ponsel dan pengisi dayanya yang cuma sepanjang satu meter, masih ada sebuah suku yang hidup sepenuhnya dari alam, menolak modernitas dan teknologi, hingga menegaskan batas dengan cara paling kuno sekaligus paling tegas yang bisa dibayangkan.
Misteri yang Nyaris Mustahil Didekati
Keterisolasian mereka bukan tanpa alasan. Pada 1880, administrator kolonial Inggris, Maurice Vidal Portman, nekat menculik enam orang Sentinel dalam upaya "menjinakkan" suku tersebut. Obsesi kolonial ini berakhir tragis. Dua orang tua meninggal karena penyakit, sementara empat anak sakit. Bodohnya, keempat anak tersebut malah dikembalikan ke pulau, membawa wabah baru ke kampung halaman. Tragedi itu, yang dicatat Portman dalam bukunya yang berjudul A History of Our Relations with the Andamanese (Vol. 2), menjadi luka sejarah yang menegaskan satu hal bagi mereka: dunia luar mutlak sumber petaka.
Bahasa mereka ibarat kode rahasia antaranggota yang tak dapat dipahami oleh suku tetangganya sendiri, seperti Onge atau Jarawa. Seorang misionaris Amerika, John Allen Chau, sempat mencatat beberapa bunyi fonetik. Dia mencatat suara tinggi "ba, pa, la, sa," yang sayangnya tak sempat diterjemahkan karena keburu tewas dibunuh pada 2018 oleh Suku Sentinel. Bahasa mereka ibarat kode rahasia yang tak akan bisa dipecahkan siapa pun di luar komunitasnya.
Dari "Gift-Dropping" ke Kebijakan "Hands Off"
Upaya mendekati Suku Sentinel terus berulang di abad modern. Antara 1970–1990, pemerintah India melalui Anthropological Survey of India (AnSI) mencoba pendekatan damai lewat metode gift-dropping—melempar hadiah dari perahu: kelapa, pisang, dan peralatan besi. Reaksinya selalu tak terduga. Kadang mereka menerima dengan senyum, kadang membalas dengan panah.
Sebuah film dokumenter tahun 1974 bahkan merekam momen absurd. Seorang pria Sentinel menembak kru film dengan panah, lalu tertawa santai di bawah pohon seolah tak terjadi apa-apa. Pada akhirnya, pemerintah India menyerah. Pada 1990-an, mereka menetapkan kebijakan hands off, eyes off, yang artinya tak boleh ada kontak langsung. Orang Sentinel cukup diawasi dari jauh saja. Pulau Sentinel pun dijadikan Cagar Suku (Tribal Reserve) dengan zona terlarang sejauh sembilan kilometer laut, demi mencegah nasib tragis seperti yang menimpa "para penjelajah" terdahulu sekaligus menjaga keberadaan Suku Sentinel agar tidak terkikis jumlahnya karena kontak paksa dari dunia luar, seperti yang dialami oleh suku-suku tetangganya di Kepulauan Andaman di masa lalu.
Selamat dari Tsunami, Bertahan dari Dunia
Saat tsunami 2004 mengguncang Samudra Hindia, Pulau Sentinel sempat dikira tenggelam. Berselang beberapa hari kemudian, helikopter India yang meninjau lokasi mendapati pemandangan luar biasa. Seorang pria Sentinel berdiri di pantai, membidik panah ke langit. Barangkali rasanya campur aduk. Merasa ditolak, sekaligus lega karena mereka masih eksis. Rupanya, di saat dunia sibuk dengan teknologi peringatan dini, orang-orang Sentinel bertahan berkat pengetahuan alam yang diwariskan turun-temurun. Mirip dengan orang Pulau Simeulue, Aceh dengan smong-nya.
Zaman Batu atau Simbol Keteguhan Identitas?
Sebenarnya, mereka bukan manusia purba yang "terjebak dalam waktu". Suku Sentinel adalah manusia modern yang memilih hidup dengan cara lama. Mereka mengandalkan pengetahuan ekologis, berburu, dan memanfaatkan logam dari bangkai kapal untuk menemuciptakan berbagai alat. Mereka mampu membuat perahu cadik, keranjang anyaman berpola rumit, dan senjata dengan ukiran geometris artistik.
Istilah "zaman batu" sesungguhnya hanyalah metafora: bukan soal keterbelakangan, tetapi soal plihan. Mereka mempertahankan wilayah, martabat, dan kebudayaan dari arus globalisasi yang kian menelan batas. Dengan membiarkan mereka hidup sebagaimana adanya, dunia justru sedang menghormati hak paling dasar manusia, yaitu hak untuk tetap menjadi dirinya sendiri.